Subuh di Waitangi sentiasa membawa sesuatu yang lebih daripada cahaya. Ia membawa ingatan.
Kabus tipis yang berarak perlahan di atas perairan Treaty Grounds seolah-olah helaian sejarah yang masih enggan dilipat, sementara air yang berkilau menyimpan gema dayung nenek moyang.
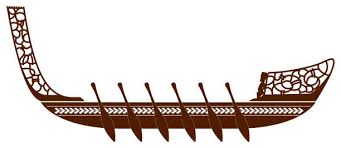
Pada pagi Waitangi 2026, ketika deretan waka besar meluncur dengan tertib
dan penuh wibawa, saya berdiri sebagai seorang Melayu yang pernah menetap enam
tahun di Aotearoa New Zealand, seorang pengembara moden yang disapa oleh masa
silam.
Waka itu bukan sekadar perahu kayu. Ia adalah taonga -- khazanah hidup. Ia membawa roh migrasi, keberanian, kepimpinan, dan perpaduan.
Setiap waka mengingatkan bahawa Maori tiba ke Aotearoa bukan sebagai pelarian tanpa arah, tetapi sebagai pelaut ulung yang memahami bintang, arus, angin, dan tanda-tanda alam.
Mereka menyeberangi samudera luas berbekalkan ilmu kolektif dan kepercayaan bahawa laut bukan pemisah, tetapi penghubung.
Ketika menyaksikan konvoi waka itu, hati saya segera kembali kepada satu kesedaran lama: Orang Melayu juga lahir daripada laut. Jauh sebelum sempadan negara, pasport, dan peta moden dicipta, leluhur Melayu sudah menganyam kehidupan mereka dengan ombak dan angin.
Laut adalah halaman depan rumah kami; pelabuhan adalah universiti terbuka; perahu adalah kitab yang mengajar erti arah dan takdir.

Di University of Waikato, ketika saya mempelajari bahasa Maori, saya mula menyedari sesuatu yang lebih dalam daripada linguistik. Bunyi vokal yang lembut, struktur suku kata yang terbuka, dan ritma bahasa itu mengingatkan saya kepada bahasa Melayu lama, bahasa pelaut yang mudah menyesuaikan diri, bahasa yang dicipta untuk dibawa angin dan air.
Ini bukan kebetulan. Maori dan Melayu berakar daripada rumpun Austronesia–Polinesia, satu peradaban maritim terbesar dalam sejarah manusia, yang menguasai lautan jauh sebelum Eropah mengenal kompas.
Dalam sejarah Melayu, laut bukan sekadar laluan dagang, tetapi medan pembentukan tamadun.
Kerajaan Srivijaya pada abad ke-7 hingga ke-13 bukan membina empayarnya dengan tembok batu, tetapi dengan penguasaan selat. Selat Melaka, Selat Sunda, dan laluan maritim Asia Tenggara.
Srivijaya memahami bahawa siapa menguasai laut, menguasai masa depan. Para pelaut Melayu membaca bintang seperti membaca doa; mereka menamakan angin, menghormati arus, dan berunding dengan alam.
Begitu juga Maori. Setiap waka yang tiba di Aotearoa membawa whakapapa, salasilah keturunan serta tikanga dan mana. Waka bukan sahaja mengangkut tubuh, tetapi juga nilai, bahasa, dan pandangan alam.
Hal ini mengingatkan saya kepada perahu Melayu yang membawa adat, pantun, dan hikayat ke pelabuhan-pelabuhan jauh: Dari Aceh ke Melaka, dari Johor ke Bugis, dari Borneo ke Kepulauan Maluku.
Apabila waka-waka itu berlabuh di Treaty Grounds, ia menegaskan Maori sebagai tangata whenua, orang asal tanah ini. Ia adalah satu pernyataan yang sunyi tetapi tegas: bahawa mereka telah lama berakar sebelum kertas perjanjian ditandatangani.
Dalam konteks Hari Waitangi, konvoi waka melambangkan perkongsian antara iwi yang berbeza, dan antara Maori dengan Mahkota British melalui Te Tiriti o Waitangi. Ia mengingatkan bahawa negara ini lahir dari pertemuan di air, bukan daripada penaklukan semata-mata.

Sebagai seorang Melayu, saya melihat persamaan yang menyentuh hati. Dalam
sejarah kami, penjajahan bermula apabila laluan laut yang terbuka kepada semua
mula dipagari kuasa asing. Portugis, Belanda, dan British memahami
kepentingan maritim Melayu dan merampasnya.
Maka perahu Melayu, yang dahulu simbol kebebasan, perlahan-lahan menjadi simbol kehilangan kedaulatan.
Di sinilah saya melihat perbezaan dan juga pelajaran daripada Maori: Mereka terus mempertahan simbol maritim mereka sebagai teras identiti, bukan nostalgia kosong.
Sepanjang enam tahun saya di Aotearoa, saya belajar bahawa budaya Maori
tidak pernah dibekukan sebagai pameran pelancong. Ia hidup di marae, di
sekolah, di universiti, dan di jalanan.
Bahasa Maori diajar dengan bangga; sejarah kolonial dibincang dengan jujur.
Saya teringat betapa berbezanya nasib bahasa Melayu klasik, bahasa pelaut dan sarjana yang kini sering dikecilkan menjadi bahasa pasar, terpisah daripada akar falsafahnya.
Konsep Maori tentang whakapapa, bahawa manusia, tanah, sungai, dan gunung berkait sebagai satu keluarga sangat dekat dengan kosmologi Melayu lama.
Dalam hikayat dan pantun, alam bukan objek mati, tetapi sahabat dialog. Gunung ada penunggu, laut ada adab, angin ada nama.
Waka yang belayar di Waitangi bukan sekadar objek budaya, tetapi pengingat bahawa manusia sepatutnya bergerak seiring alam, bukan melawannya.
Konvoi waka juga mengajar tentang kepimpinan kolektif. Tiada satu dayung yang lebih penting daripada yang lain. Semua mesti seiring, mengikut irama yang sama.
Ini mengingatkan saya kepada perahu layar Melayu yang memerlukan kesepakatan penuh jika seorang alpa, perahu boleh terbalik.
Dalam dunia moden yang memuja individualisme, simbol ini terasa semakin relevan. Bangsa yang lupa mendayung bersama akan hanyut, walaupun kapalnya besar.

Waitangi 2026, dengan ribuan manusia di tebing air, adalah cermin pada masa lalu yang masih hidup. Ia bukan sekadar upacara tahunan, tetapi ruang muhasabah nasional.
Saya melihat kanak-kanak Maori berdiri dengan bangga, menyanyi dalam bahasa ibunda mereka, dan saya terfikir tentang anak-anak Melayu: sejauh mana mereka mengenal laut sebagai akar peradaban, bukan sekadar lokasi percutian?
Bagi saya yang pernah diterima sebagai sahabat oleh komuniti Maori, persahabatan itu lahir daripada kesediaan untuk mendengar. Saya datang bukan sebagai pakar, tetapi sebagai pengembara yang mengakui kejahilan.
Dari situ, saya belajar bahawa hubungan antara budaya tidak boleh dibina atas rasa lebih tahu, tetapi atas rasa ingin memahami.
Apabila saya menyaksikan waka-waka itu tiba, saya juga melihat bayang perahu Nusantara -- jong besar Melaka, pinisi Bugis, dan perahu layar Orang Laut.
Saya melihat nenek moyang Melayu yang pernah menjadi penghubung dunia Timur dan Barat, sebelum sejarah ditulis semula oleh penjajah.
Laut yang sama yang membawa Maori ke Aotearoa juga pernah membawa Melayu ke Madagascar, membuktikan bahawa peradaban maritim kita pernah menjangkau separuh dunia.
Maka Waitangi, bagi saya, bukan sekadar hari kebangsaan New Zealand. Ia adalah peringatan global bahawa tamadun maritim pernah mengajar manusia tentang keseimbangan, kerjasama, dan hormat kepada alam.
Waka itu berbicara kepada sesiapa yang sanggup mendengar: bahawa kemajuan tanpa akar hanya akan menghasilkan bangsa yang lupa arah.

Selagi air terus mengalir, waka akan terus belayar. Ia membawa pesan bahawa sejarah bukan untuk disimpan di arkib, tetapi untuk dihidupkan dalam tindakan.
Sebagai seorang Melayu yang pernah hidup di Aotearoa, saya percaya bahawa kita di mana pun berada perlu kembali belajar mendengar laut. Kerana di situlah tersimpan jawapan tentang siapa kita, dari mana kita datang, dan ke mana kita seharusnya menuju.
Dan pada pagi Waitangi 2026, ketika dayung-dayung itu menyentuh air
serentak, saya tahu: Perjalanan ke hadapan hanya bermakna jika kita mendayung
bersama dengan ingatan, dengan hormat, dan dengan jiwa maritim yang tidak
pernah benar-benar mati. - KitaReporters










